CRITICAL THINKING
Alhamdulillah tanggal 17 April kemarin Pemilu udah
diselenggarakan di Indonesia, meski siapa yang akan jadi Presiden
masih bakal diumumkan secara resmi sebulan lagi.
Sungguh sejujurnya saya sudah lelah dengan segala hal yang
ada di social media, terutama tentang politik. Orang-orang berlomba mematahkan opini politik orang lain seakan jadi yang paling benar preferensi politiknya, sampai-sampai kadang
kaya ga pake hati ngomong soal A, B, atau C. Miris banget.
Salah satu hal yang bikin saya kepengen semua hal ini cepat
berakhir adalah karena merasakan sendiri betapa sensitifnya teman-teman di social
media tentang isu-isu pemerintahan. Bahkan karena mengkritik tentang satu sistem dalam bidang kesehatan, suami saya sampe diblock sama temennya. Sedih sih,
padahal mungkin juga itu masukan yang bagus semisal yang bersangkutan open
minded dan ga temperamen pakai kepala panas membaca pendapat orang lain.
Makin kesini saya sebenernya juga makin mikir… Skill apa
yang harus anak saya miliki besok, kalau kondisi dan situasi masih kaya gini,
or even worse, lebih buruk dari sekarang?
Saya rasa, anak-anak Indonesia perlu diajarkan lebih serius
tentang critical thinking atau berpikir kritis. Ini yang masih kurang dimiliki orang dewasa jaman now, yang akan sangat lebih baik kalau generasi kita selanjutnya punya keterampilan ini mulai dari kecil.
Cerita pribadi saya,
Saya lahir dari keluarga besar. Dua orangtua lengkap dan tujuh anak. Semuanya pernah melalui masa kecil yang berbeda-beda: kakak pertama saya mungkin merasakan sendiri sulitnya orangtua saya hidup dan berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga adik bungsu saya yang dari lahir sudah merasakan fasilitas yang mumpuni karena taraf hidup keluarga kami saat itu lebih dari baik, dan kondisi ekonomi lebih dari mapan.
Tapi kami semua mengalami pasang surut kehidupan bersama, dari mulai krisis moneter 1998 di mana toko kami yang jadi sumber penghasilan satu-satunya terbakar dalam kerusuhan, harus jualan lontong opor setiap Minggu pagi di Manahan, banjir tahun 2007, dan ga perlu diceritakan disini masalah internal keluarga yang ga cuma sekali dialami bersama. So it's safe to say that we have been together for the ups and downs.
Dari semua pengalaman itu, patuh pada orangtua ada di prioritas teratas. Kami istilahnya benar-benar harus mengikuti apa kata Papa dan Ibu, karena itu pasti jalan paling baik dan satu-satunya cara ga merepoti mereka lagi di tengah kesibukan membesarkan tujuh anak. Papa adalah opinion leader kami, jelas. Semua yang keluar dari mulut papa itu kebenaran yang ga bisa dibantah, selain karena Papa emang beneran pinter dan suka baca, anak-anaknya ga ada yang punya cukup nyali untuk mengkritisi.
Saya bersyukur atas semua yang udah dilakukan orangtua saya. Mungkin dari tulisan saya diatas, orangtua saya terdengar seperti ortu yang otoriter. Padahal ya engga juga, mereka sering kali juga memberikan keleluasaan kami dalam memilih: Saya mau masuk jurusan komunikasi daripada mode, pilih UNS daripada UGM yang padahal waktu itu udah diterima, milih lanjut sekolah lagi di ESMOD, sampai milih mau bikin clothingan sendiri lalu memutuskan jadi Ibu Rumah Tangga. Semua diserahkan kepada saya sendiri, tanpa adanya keharusan dari mereka.
Tapi satu hal yang saya masih rasakan sampai sekarang adalah, keluarga saya tidak terlalu mengedepankan pemikiran kritis. I barely remember kapan terakir kali kami tidak setuju akan satu hal serius dan berdiskusi secara sehat tentang hal itu (sebelum saya dewasa). Pendapat berbeda selalu dianggap sebagai potensi konflik, ga seru, ga kompak, dll. Mungkin ini juga seni-nya punya sodara banyak ya, haha. Hal ini terbawa hingga dewasa, saat saya kurang sreg akan suatu keputusan atau perilaku saudara saya, saya menghindari bicara langsung. Kadang diempet, atau dirasani sama anggota keluarga lain. Kalo diomongin langsung bisa canggung, bisa gak enakan, bisa-bisa nanti ga mau cerita lagi.
Saya pikir-pikir lagi mungkin setiap kali mengambil keputusan besar dalam hidup dan nanya pendapat sama keluarga, mereka selalu terlihat setuju-setuju saja. Ga ada opini kontra atau hal lain yang jadi bahan pertimbangan, apa jangan-jangan karena anggota keluarga yang lain juga mikir sama? Ga mau jadi masalah, biar aja konsekuensi ditanggung nanti, yang penting tanggung jawab dulu sama pilihannya.
Ini yang saya gamau kalo sampe Alyaka melakukannya. Punya atau tidak punya nanti dia saudara kandung.
Alya harus bisa dan boleh membantah (dengan santun) pendapat Ayah Ibunya. Alya harus berani mengutarakan opini pribadinya tanpa harus takut setelah itu saya cemberutin. Alya harus bisa mengelaborasi pemikiran di kepalanya dengan baik, tanpa takut nanti saya sindir-sindir atau saya mentahkan dengan opini yang childish, diluar konteks, dan tidak substansial. Alya harus berani berpendapat dan mempertanggungjawabkan opininya, jika ternyata kurang tepat dia harus meminta maaf, jika dirasa benar dia tidak boleh jumawa. Alya harus selalu ponders, bertanya, mencari tahu how? why? what? agar kelak dia tidak bisa disetir dan digiring seenak orang lain, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya.
Banjir informasi menuntut kita untuk mempunyai stand point namun tetap fleksibel dengan opini lain. Hal yang prinsipil mesti jelas, sedangkan point of view mesti luwes. Jangan sampai Alya terlalu mengidolakan Ayah atau Ibunya dan manut-manut saja saat kami beropini A. Lalu saat oranglain mengkritisi, dia sakit hatinya seakan-akan Ayah Ibunya dipermalukan dan didzholimi :p
Tanpa critical thinking, kita hanya akan membesarkan anak yang kelak jadi tua, namun tidak dewasa.


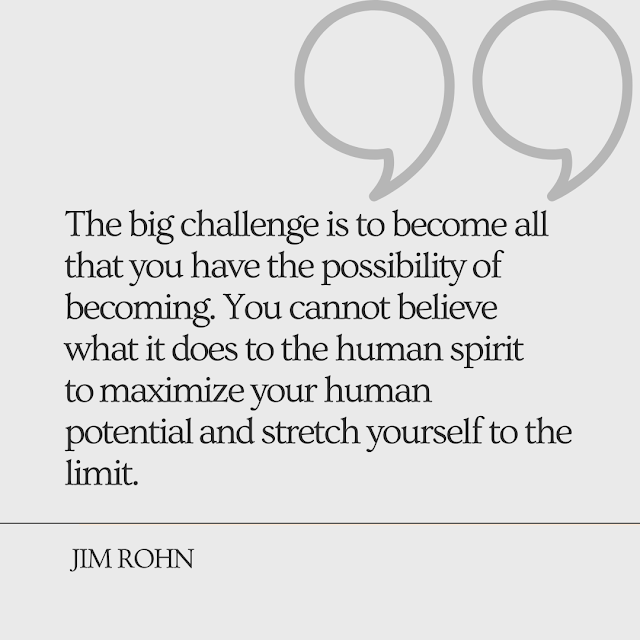
Comments
Post a Comment